Mengubah dari Bawah; Cerita yang Diulang
Judul Buku : Hidup di Atas Patahan
Penulis : Anwar Jimpe Rachman
Penerbit : Insist Press
Tebal Buku : iv + 110 hlm
Buku ini dengan bahasa ringan menarasikan pengalaman dan perjuangan
penanganan bencana di Bengkulu Utara, Sinjai, dan Tual (Maluku Tenggara). Buku
ini menceritakan heroisme dan perjuangan inspiratif dari orang-orang dan
beberapa lembaga akar rumput yang ‘bergerilya’ mencari solusi pencegahan
bencana di daerah basis kegiatan mereka.
Tiga hal menarik bagi saya yang wajib dikabarkan dari buku ini
adalah heroisme para penggiat basis ini, peran negara dan birokrasi rumit, dan
inisiatif rakyat itu sendiri.
Pertama, saya ingin memberikan
klaim bahwa aktivitas para penggiat dan pemerhati masalah akar rumput ini
adalah sebuah bentuk heroisme yang langka. Nama-nama yang disebut dalam buku
ini, bersama masyarakat dan staf pemerintahan, merancang formula bagi
pencegahan bencana di lokasi masing-masing.
Lihat saja apa yang dilakukan
Nurkholis Sastro dan Hambali di Bengkulu Utara, salah satu daerah yang paling
rentan gempa dan tsunami di Indonesia. Sastro bersama Hambali (Mitra Aksi)
berjuang memasukkan materi kebencanaan sebagai mata ajar muatan lokal di dalam
kurikulum pendidikan di Bengkulu Utara.
Cerita dari Sinjai senada. Ada
sosok Pak Daming, pembiak tanaman organil dan pengajar di SMP Satap Tassoso,
yang menjadi ‘rekan’ lokal tim Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Payo-Payo.
Persoalan birokrasi menjadi tantangan lain bagi usaha tim PRB Payo-Payo ini
bersama dengan kepentingan politik yang sangat acak dan momentum Pilgub Sulsel.
Sedangkan di Maluku Tenggara, ada
cerita perjuangan Fritz Elmas dan Uly dari Yayasan Nen Mas Il, bersama Pak Nor,
Edo Rahail, dan Pieter Elmas. Kisah suksesnya: mereka berhasil menarik simpati
lembaga legislatif, DPRD Maluku Tenggara hingga mampu terus mendesak pemerintah
daerah untuk memperhitungkan aspek kearifan
lokal dalam berbagai
bidang kegiatan masyarakat maupun pemerintah. Meski tetap saja mereka mendapat
tantangan dari paradigma proyek pemerintah dan seringnya tidak nyambung dengan
kebijakan pemerintah pusat.
Semua itu menjelaskan bahwa ada
sekelompok manusia yang berniat bekerja dan belajar bersama orang kecil dan
membuat perubahan-perubahan sederhana namun bermakna. Kisahnya sangat kecil
kemungkinan untuk dikabarkan jika mengharapkan media massa untuk melakukannya. Media
cenderung mengangkat berita bencana ketika telah terjadi dan membawa
korban–istilah buku ini “paradigma keperistiwaan”, bukan menyorot cerita sukses
pencegahan dan pembangunan pola pikir baru berdasarkan kearifan masyarakat.
Kedua, peran negara dan
birokrasinya yang sangat rumit menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi
para hero dalam
buku ini. Menyoroti ini, tiga hal penting yang bisa dicatat dalam buku ini,
yakni kapasitas negara (pemerintah) yang tidak mengenal dan memahami
wilayahnya, paradigma proyek pemerintah dalam menjalankan tugas, dan kesan
lepas tangan dari masalah bencana pasca-proyek, dan tentu saja birokrasi
berbelit.
Cerita di Sinjai dan Maluku
Tenggara mungkin bisa mewakili catatan pertama. Tahun 1980-an, pemerintah
mencanangkan program berlabel “Sejuta Pinus” di Kompang, Sinjai, daerah yang
berkemiringan ekstrem. Bagi pemerintah, program ini bisa berarti sebagai upaya
pemberdayaan lahan yang ditinggalkan warga akibat pemindahan paksa ke tepi
jalan untuk kepentingan strategis pengawasan militer pada masa DI-TII. Selain
itu, tentu saja getah pinus merupakan komoditas berharga bagi pengusaha karet
nasional kroni Orde Baru masa itu. Namun demikian, dampaknya baru terasa
sejalan 20 tahun program tersebut ketika daerah Kompang yang tingkat
kemiringannya tinggi tersebut menjadi neraka akibat longsor pada tahun 2006
silam.
Membandingkan ide “Sejuta Pinus”
pemerintah dan argumen orang kecil seperti Pak Asikin Pella, tampak tidak fair. Meski demikian, ada logika lain yang terbangun
dalam ucapan Pak Asikin, bahwa sesungguhnya pohon pinus merupakan tumbuhan yang
bisa merubah siklus air dikarenakan struktur akar tunggangnya yang menancap ke
tanah. “Dengan begitu, tanah menyerap air, yang dengan demikian sewaktu-waktu
air tertampung banyak sehingga menyebabkan retak/pecahnya tanah,” begitu dalih
Pak Asikin (hl. 66).
Di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara
yang terbentuk dari pulau-pulau atol kini
harus menghadapi ancaman kekurangan air bersih akibat pertumbuhan populasi dan
permukiman berikut semakin dibukanya lahan hutan. Sementara itu, pemerintah
meresponnya dengan mengirimkan bibit jati putih yang merupakan tanaman penyerap
air yang banyak. Blunder pemerintah ini bisa saja menspekulasikan berbagai
motif, namun tetap perlu pembuktian lebih. Hal terpenting yang bisa dipetik
dari cerita ini bahwa pemerintah masih saja angkuh dan merasa lebih mengerti
seluruh dunia daripada orang-orang kecil yang bergulat dengan praktik kearifan
lokal berbasis pengalaman puluhan hingga ratusan tahun di kesehariannya.
Kedua cerita di atas juga
sekaligus ingin menunjukkan paradigma dan pendekatan penyelesaian masalah
pemerintah dalam kebencanaan yang (masih) berpola proyek. Ketimbang
memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan dukungan bagi rencananya,
pemerintah memilih menjalankan sendiri programnya.
Lelucon lebih parah terjadi di
Bengkulu Utara ketika pada tahun 2011, Pemerintah Bengkulu membangun gudang
logistik yang kemudian ditolak oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Penolakan itu didasarkan pada lokasi bangunan yang hanya berjarak seratus meter
dari bibir pantai, pembangunan yang melanggar UU Pokok Kehutanan No. 41 tahun
1991 tentang sempadan pantai. Pembangunan gudang logistik di tepi pantai daerah
yang rentan gempa dan tsunami benar-benar lelucon pemerintah dan hanya
menampakkan ketidakseriusan negara dalam pencegahan bencana.
Kedua catatan tersebut menjadi
semakin rumit jika dihadapkan pada persoalan birokrasi. Persoalan mutasi
sebagai wajah baru birokrasi di Indonesia akibat Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) berimbas kepada pendekatan ‘dari-nol-lagi’ terhadap aparat pemangku
kebijakan sebagaimana dikeluhkan oleh Fritz Elmas, Uly, dan Pak Nor di Maluku
Tenggara. Pak Nor, aparat BPBD Maluku Tenggara, bahkan galau karena pengetahuan
penangann dan pencegahan bencana akan ‘menguap’ begitu saja akibat mutasi.
Kegelisahan yang sama mungkin
dirasakan juga oleh tim PRB Payo-Payo di Sinjai. Betapa tidak, berbagai
kegiatan yang mereka lakukan haruslah mendapat izin atau paling tidak
sepengetahuan para pengambil kebijakan Kabupaten Sinjai. Persoalannya adalah
kesepahaman yang tidak pernah terjadi di antara mereka dikarenakan dua hal.
Pertama, jarang hadirnya pihak pengambil kebijakan dalam setiap rangkaian
kegiatan ataupun pertemuan PRB. Kedua, arogansi dan mentalitas feodal pihak
pengambil kebijakan tersebut yang menolak mendapatkan wawasan dan ide segar
dari generasi yang lebih muda. Buku ini mengutip kalimat ketus petinggi Pemda
Sinjai bahwa “Dalam adat kita, seorang anak tidak pantas mengajari
orangtuanya!”(hl. 54).
Meski demikian, harus diakui
tetap saja ada orang-orang yang memiliki kepedulian di dalam lingkaran
pemerintah dan birokrasinya yang serba berliku. Kita tentu tidak melupakan
sosok Pak Nor, aparatur BPBD Maluku Tenggara, mantan staf Dinas Pekerjaan Umum,
dan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang sudah dibicarakan dari
tadi. Di tanah yang sama, ada Pieter Elmas dan Edo Rahail yang mendukung penuh
kegiatan dan usaha pencegahan dan penanganan bencana di Maluku Tenggara. Di
Bengkulu Utara, ada Kardo Manurung, Kepala SMA 1 Lais, bersama guru-guru yang
dinaunginya yang berjuang memasukkan unsur kebencanaan sebagai materi ajar
muatan lokal di dalam kurikulum pendidikan sekolah di Bengkulu Utara. Kita
tentu tidak melupakan kerja keras Pak Daming, Ibu Guru Anti, Pak Bahar, Kasim,
dan yang lainnya di Sinjai.
Ketiga, hal terakhir yang ingin
saya catat di sini adalah penegasan inisiatif dari bawah masih merupakan metode
paling efektif dalam menggerakkan perubahan. Hal ini tentu saja berdasarkan
pada gagasan sederhana: mereka yang bekerja lebih dekat dengan objek lebih
memahami dan mengerti kebutuhan mereka untuk bertahan dan melanjutkan hidup.
Dengan sendirinya, akan terbentuk kearifan-kearifan berikut nilai dan pranata
untuk menjamin kelangsungan kehidupan tersebut dan melindunginya dari ancaman.
Namun, tentu saja ada keserakahan
manusia lain yang senantiasa mengincar. Apalagi yang melatarinya kalau bukan
motivasi ekonomi. Dengan restu kekuasaan, maka atas nama perubahan, kemajuan,
dan modernisasi, kearifan berikut sistem nilai dan pranatanya tersebut menjadi
target untuk dimusnahkan.
Perubahan sejatinya lahir dari
gerakan dan inisiatif sederhana berbasis kebutuhan masyarakat. Bukankah
masyarakat yang merasakannya lebih mengerti kebutuhan sendiri?[]
Penulis: Saharuddin Idris
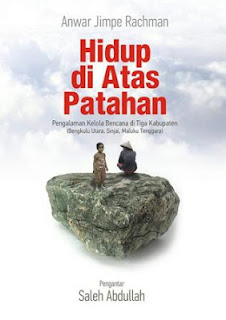


Komentar
Posting Komentar