Guru dan Buku
TAHUN 2013 saya bertemu lagi dengan Mochtar Pabottingi. Kali ini lewat buku berjudul Burung-Burung Cakrawala (Gramedia, 2013). Buku autobiografi itu ia tulis sendiri—hal yang memang dilakukan orang semampu, sepatut, dan sebentangan-cakrawala berpikir sekaliber lelaki dari Bulukumba ini.
Burung-Burung Cakrawala (BBC) terdiri dari delapan bab. Meski setebal 386 halaman, tapi saya menikmatinya sekisar tujuh hari saja. Itu pun saya melewatkan membacanya lantaran bersibuk di luar rumah hingga larut.
Setiap babnya bercerita tahapan kehidupan Mochtar Pabottingi. Pak Mochtar membuka cerita bagian pertama tentang masa kecilnya di sebuah rumah panggung di Desa Barebba, nama kampung di Kabupaten Bulukumba, yang terletak di pinggang pegunungan kawasan Lompobattang.
Pada bab kedua, Pak Mochtar bercerita perihal kepindahan keluarganya ke Makassar pada tahun-tahun akhir dasawarsa 1950. Sayup tertangkap dalam bagian ini narasi tentang kepindahan banyak orang ke Makassar dikarenakan dera perang antara TNI dan DI/TII. Sengketa ini pula menjadi salah satu episentrum pendorong gelombang migrasi orang-orang Sulawesi Selatan ke Makassar maupun ke daerah lain.
Dalam bab ini kita bisa meresapi romantisme keadaan Makassar kala belum menjadi kota semacet sekarang. Lebih dari itu, di sepanjang bab ini berikut dalam End Note [Catatan Akhir] saya mendapat banyak informasi bagaimana golak dan didih dunia intelektual di Makassar di kurun waktu 1970-an dan gemanya yang menyentuh kita hingga sekarang.
Bab-bab setelahnya menghikayatkan bagaimana ia menjelma sebagai seekor burung membentangkan sayapnya menuju ufuk-ufuk yang sering dibayangkan oleh Mochtar muda tatkala duduk menghabiskan senja di Pantai Losari tahun 1960-an.
Cakrawala pertama adalah Yogyakarta. Pak Mochtar menjejaki Yogya berkat beasiswa dari sebuah perusahaan multinasional. Di sana ia melanjutkan jurusan Sastra Inggris di UGM, yang sebelumnya ia sempat tempuh di Unhas, Makassar. Di sini ia berkarib seraya berguru pada sejumlah nama ‘awam’ di jagat kecendikiawanan Indonesia, seperti Umar Kayam, Kuntowijoyo, WS Rendra, dll. Bab ini pun dijuduli “Yogyakarta: Merapat ke Orbit Bintang-Bintang”.
Jakarta lalu menjadi cakrawala kedua yang dijelajahi Pak Mochtar. Ia bertemu lagi Rendra karena kerap tampil berteater di TIM (Taman Ismail Marzuki). Pak Mochtar sering mengunjungi Rendra dan Mas Kunto kala di Yogya, sebagaimana juga ia sowan ke rumah Taufik Ismail dan Sapardi Djoko Damono saat bermukim di Jakarta. “Murni karena daya magnit dari keempat sastrawan papan atas ini.” [hal. 147]
Kurun waktu bab ini pada dasawarsa 1970, masa Pak Mochtar meniti karir. Kala itu pula intelektualitas di Yogyakarta dan Jakarta berkembang pesat ditopang fondasi penerbitan yang kokoh. Pak Mochtar paling sering mengunjungi Horison dan Prisma. “Jika Horison menjadi barometer kesusastraan, Prisma menjadi barometer perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia.” [hal. 153] Masa itu memang zaman ketika Jakarta menjadi pusat kehidupan penulis, seniman, dan intelektual Indonesia. Selain Horison dan Prisma, terbit pula Kompas, Tempo, Budaja Djaja, menjadi semacam komunitas media yang melahirkan kalangan-kalangan tadi.
Pak Mochtar juga menuturkan pengembaraannya ke cakrawala Amerika Serikat di bab selanjutnya, negeri yang dijajalnya karena harus melanjutkan studi. Agaknya selama di Amerikalah salah satu bagian hidup Pak Mochtar ditempa. Justru di negara nun jauh ini ia mendapati perbandingan Islam yang diyakininya dengan Islam versi rekannya sesama penuntut ilmu dari negara lain. Islam bagi Pak Mochtar adalah Islam agama damai dan tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, sebagaimana yang dinarasikannya tentang satu hari bulan puasa di Amerika.
BUKU INI pun lahir dari dorongan seorang guru. Guru itu bernama Drs. Wirono, dosen jurusan Sastra Inggris UGM, tempat Pak Mochtar menuntut ilmu empat puluh tahun silam. Pak Wirono rupanya juga membaca narasi Pak Mochtar “Dari Rumah, Karakter, Dari Buku, Cakrawala” dalam Bukuku Kakiku (PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). Pak Mochtar menulis dalam Tulis Terima Kasih bahwa Pak Wirono menyuratinya lewat pos yang berisi permintaan agar mantan mahasiswanya itu mengembangkan narasi itu dan menerbitkannya dalam buku tersendiri. [hal.373]
Justru penjelasan ini menjadi salah satu kalimat di buku ini yang mengharukan bagi saya. Betapa Pak Wirono tetap menjadi seorang guru bagi Pak Mochtar. Saya lantas pikir, di bagian seperti inilah yang kita butuhkan dari seorang guru: mengajak kita menggali bongkahan intan dalam diri kita.
Ingatan saya lalu tertaut pada seorang dosen kala saya mahasiswa dulu. Ia terkenal ‘galak’. Namun saya tak bisa melupakannya. Bukan karena tempramennya yang tak tertebak, melainkan cara dia mengajar. Ia membantu saya menggali apa saja yang masih terpendam dalam diri. Dalam setiap ujian, ia sangat sering memberi kita ‘soal-soal terbuka’—pertanyaan yang mengajak kita menganalisa dan menggeledah seluruh hasil bacaan dan nalar kita. Soal ujian seperti itu saya butuhkan. Masa sekolah dulu [mungkin sampai sekarang] jamak kita temui soal-soal pilihan ganda—pertanyaan yang menyediakan jawaban yang ‘benar’.
SAYA SENGAJA menggunakan panggilan “Pak Mochtar” untuk menyebut Mochtar Pabottingi sejak awal tulisan ini. Saya menganggapnya guru. Mohon jangan bayangkan Pak Mochtar akan berdiri di depan kelas. Kami hanya bertemu tiga kali saja sebelum saya bersua buku ini.
Pertemuan kali pertama saya dengan Pak Mochtar lewat narasi “Dari Rumah, Karakter, Dari Buku, Cakrawala” pada tahun 2005. Baru dua tahun kemudian saya bertatap muka langsung. Pak Mochtar yang selama ini menjadi bintang bersinar di bentang langit sana karena keluasan pengetahuannya, sekarang ia menjabat tangan saya langsung. Ia hadir di Komunitas Ininnawa kala itu atas undangan teman untuk berdiskusi tentang politik. Terasa benar wibawa dan kharisma Pak Mochtar di situ. Ketegasan sikap ia utarakan kala saya ingin menyerahkan naskah kumpulan sajak Aslan Abidin untuk ia baca dan komentari. Antologi itu rencananya segera diterbitkan Ininnawa. Namun, dengan alasan tertentu, Pak Mochtar menolak. Sungguh saya memaklumi alasan yang disampaikan Pak Mochtar malam itu.
Pertemuan kedua saya di acara MIWF. Pak Mochtar masih tegap. Rambutnya yang berombak kian banyak memutih. Saya harus duduk dipanel dengan Pak Mochtar membincangkan warisan kerja-kerja kecendikiawanan Mattulada—sebuah hadiah besar bagi saya karena bisa duduk bersanding dengan seorang analis politik terkemuka Tanah Air.
Sebagaimana pertemuan awal, saya mendapati lagi penjelasan lisan Pak Mochtar yang persis bagaimana bila ia menuangkannya dalam tulisan. Ujarannya tersusun rapi dengan bahasa Indonesia yang begitu prima. Amat jarang saya mendapati orang seperti itu, lisan dan tulisan bagai saudara kembar.
Tatap muka itu, maupun kemudian lewat buku yang ditulis sang guru ini, menyadarkan saya akan kebodohan dan kepandiran sendiri. Lisan dan tulisan sepadu itu bukan semata karena kecendikiawanan, melainkan juga perihal penghormatan untuk ‘guru-guru’ sebelumnya.
“… Selalu kuusahakan untuk merujuk dan mengutip secara jujur dan teliti hingga ke ejaan, tanda baca, dan empasis… Aku menghormati teks dan penulisnya sekaligus. Begitu tiap penulis unik dan nyata…” [hal. 303-304]
Ya, pertemuan ini memang lewat buku. Tapi Pak Mochtar, kali ini, lebih menyata. Dia ada di depan saya.[]
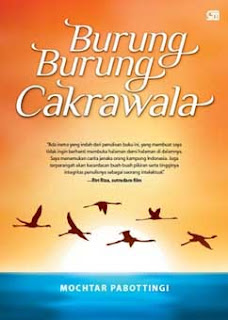


Komentar
Posting Komentar